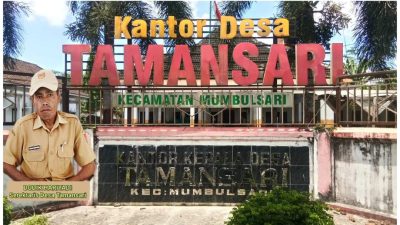WAHIDIN DAN REL KERETA API KEMATIAN
Denny JA
(Di tahun 1942-1945, Jepang mengerahkan rakyat Indonesia kerja paksa membangun rel kereta api. Panjang rel itu 220 km, dari Sumatra Barat ke Riau. Lebih dari 100 ribu pekerja paksa itu mati merana. Joko, pekerja paksa yang masih hidup bercerita)
-000-
Januari 1999, usia Joko 81 tahun.
Badannya kurus kering.
Tapi ingatannya masih tajam.
Sekitar 25 mahasiswa jurusan sejarah, bersama dosen,
mengunjunginya.
Mereka ingin mendengar kisah romusha dari pelaku langsung.
“Kami bekerja di tempat yang buas,
di hutan belantara yang luas, melewati sungai yang deras,
menembus bukit keras,
masuk ke rawa- rawa dan batu cadas.” (1)
“Ada teman saya mati dimakan biawak.
Ada yang wafat diterkam singa.
Lebih banyak mati karena nyamuk malaria.”
“Mayat mereka dibiarkan saja membusuk di pinggir sungai,
atau di tepi jalan rel kereta.”
Maya, mahasiswi yang hadir di sana, melihat air mata menetes di pipi Joko.
Air mata itu bewarna gelap, karena kelamnya memori masa silam.
Dari mulut pak Joko,
dilihatnya seolah ratusan kelelawar, dari gua yang purba,
berterbangan keluar, meraung- raung karena luka, mencari langit yang bebas.
“Saya dari Jawa.
Dikirim ke sini, ke Sumatra Barat, bulan April 1943.
Rombongan saya lebih dari 10 ribu orang.
Usia saya 15 tahun.
Wahidin mengajak saya ke sini.
Katanya, kita harus bantu Jepang.
Ini Rel kereta penting untuk pembangunan.
Untuk angkut kayu,
batu bara,
karena perang perlu uang.
Nanti Jepang bantu Indonesia merdeka.
Jepang saudara tua kita.
Tapi saudara tua kok kejam sekali.
Kami kadang dikasih makan, sekali sehari.
Hanya segepok nasi pakai garam.
Itu orang Jepang,
mengawasi kami bekerja.
Kami dipecut, dipopor.
Kami harus gesit, katanya.
Rel kereta api harus selesai cepat.
Dalam tiga bulan saja,
badan saya dan Wahidin, kurus kering.
Tulang- tulang kelihatan, seperti tengkorak.
Tapi Wahidin selalu beri semangat.
Rel kereta api ini
punya kita.
Jepang akan pergi.
Sabar saja.
Yakin saja.
(Para mahasiwa mendengar kisah itu dengan khusyuk.
Angin bertiup pelan di beranda rumah tua itu, membawa rahasia masa silam yang lama terkubur)
“Kerja saya memasang dinamit di bukit batu, di tepian sungai.
Tapi yang tak tahan,
Saya juga disuruh Jepang membersihkan lokasi dari mayat teman- teman yang bergelimpangan.
Jepang melarang kami mengubur mayat.
Katanya, itu buang- buang waktu.”
Tapi saya dengar,
tentara Jepang juga membuat kuburan massal,
karena bau mayat menyengat.
Mengganggu kerja.
Waktu Wahidin mati,
Saya nekad.
Malam hari, diam- diam,
saya dan teman- teman menguburkannya.
Kami berdoa khusus.
Saya kasih tanda kuburannya.
Tapi waktu banjir,
kuburan itu juga hilang.
“Mengapa Wahidin mati?,”
tanya seorang mahasiswa?
Jelas Joko: Wahidin itu sakit- sakitan.
Ia kena beri- beri, disentri,
juga digigit nyamuk malaria•
“Badan Wahidin ringkih,
tapi orangnya pinter,
sangat ingin Indonesia merdeka.
Wahidin itu pemimpin kami.
Selalu beri kami semangat.”
Lanjut Pak Joko:
“Itu jejak rel kereta api, sudah tak ada.
Jembatannya roboh.
Besi rel kereta dijarah penduduk.
Juga kayu- kayunya.
Habis, dijarah.”
“Saya lebih sedih lagi,
kata Pak Joko.
Wahidin mati sia- sia.
Rel kereta api yang ia banggakan
sudah tak ada.
Maya melihat kejauhan,
dari ujung ke ujung.
Rel kereta api maut itu, memang tak ada lagi jejaknya.
Tapi, tekad Maya,
kisah sedih ratusan ribu pekerja paksa ini, jangan pula hilang tanpa jejak.
Maya mengajak teman- teman mahasiswa, tabur bunga.
Seraya berdoa,
agar kerja paksa itu jangan lagi terjadi.
Maya sendiri menabur bunga di sungai yang deras.
Untuk pekerja yang mati di sungai itu,
dimakan buaya,
dimakan biawak.***
Jakarta 10 Mei 2024
CATATAN
(1) Kisah pekerja Romusha ini diinspirasi dari berbagai catatan sejarah. Antara lain berita ini: